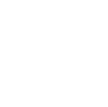ETOS KERJA MUSLIM DARI PERSPEKTIF KULTURAL
Dibaca: 5237
Penulis :
ETOS KERJA MUSLIM DARI PERSPEKTIF KULTURAL
Mohammad Damami
I
Berbicara tentang etos kerja muslim, apalagi dipertajam dengan frasa “perspektif kultural”, tidak terlepas dari paradigma hubungan antara “agama” dan “masyarakat pemeluk” dari agama yang bersangkutan. Karena dalam pembahasan ini dibatasi di kalangan komunitas “muslim”. Maka tentu saja masalah etos tersebut perlu dibaca hubungan korelasi antara “agama Islam” di satu sisi dan “umat Islam (muslim)” di sisi yang lain. (cf: Ali, 1975:44)
Pernyataan perlunya pembacaan hubungan korelatif di atas merupakan salah satu konsekuensi logis dari perlunya faktor tafsirandalam proses penyusunan konsep ajaran agama. Sebab, yang dikembangkan dalam Islam, di samping agama ini memang memberikan ruang berpikir secara induktif, namun ruang berpikir deduktif tetap yang dipentingkan. Bahwa ukuran kesalehan kerja seorang mukmin/muslim tetap diukur secara deduktif tersebut (QS At-Taubah, 9:105). Dari sinilah budaya ijtihad memiliki kemestian untuk memperoleh tempat yang kuat. Dengan budaya ijtihad yang terus menerus terpakai semacam itu akan memungkinkan terhindarnya pembentukan otoritas yang bersifat imun kritik atau kelembagaan yang bersifat absolut. Oleh karena itu rumusan konsep yang dihasilkan dapat secara terus menerus dikoreksi secara deduktif-induktif di atas.
Bahwa sebenarnya pencarian dan penemuan konsep yang diperlukan oleh zaman, semestinya tidak harus menanti datangnya tantangan (challenge) baru ada tanggapan (response), melainkan sudah menjadi kemestian. Di sinilah akan ditemukan bukti, apakah umat Islam mampu lebih banyak “mengubah” keadaan atau justru malahan banyak diubah oleh keadaan. Pro aktif dalam menegakkan budaya ijtihad kiranya perlu dijadikan sebuah “karakter” dalam zaman globalisasi ini.
II
Ada hal yang cukup menarik kalau dilakukan perbandingan antara kondisi umat Islam zaman Rasulullah Saw yang waktu itu umat Islam masih “baru lahir”, dan kondisi umat Islam pada masa globalisasi ini, yang boleh dikatakan umat Islam “sudah dewasa”. Pada zaman Rasulullah Saw yang wilayahnya tentu saja masih terpusat di Makkah dan Madinah, terdapat dua kekuatan geopolitik dan geoekonomi yaitu Romawi (Bizantium) yang memonopoli kepemimpinan di “bagian Barat” dan kekaisaran Persia yang memonopoli kepemimpinan di “bagian Timur”. Romawi dapat hebat karena adanya faktor peradaban “Yunani” (Khan, 1985:19), sedangkan Persia menjadi hebat karena adanya faktor “kuatnya kekuasaan yang dibungkus oleh agama”, yakni dengan keyakinan bahwa “darah Tuhan mengalir dalam pembuluh venanya (pembuluh darah para Kaisar yang diberi gelar Kisra atau Chosroe)”. (Khan, 1985:21-22). Pertarungan dua kekuatan geopolitik dan geoekonomi telah disinggung secara resmi dalam al-Qur’an (QS. Al-Rum, 30: 2-3).
Zaman kini zaman globalisasi, umat Islam yang wilayahnya sudah begitu luas, terutama di sekitar Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, juga tempat tinggal mereka telah tersebar di seluruh permukaan planet bumi, menghadapi dua kekuatan geoplotik dan geoekonomi yang besar pula, yaitu Eropa dan Amerika untuk monopoli kepemimpinan di “Barat” dan India serta Cina untuk (kemungkinan) monopoli kepemimpinan di “Timur”. Bedanya adalah, kalo pada zaman Rasulullah Saw. ilmu, teknologi, transportasi dan komunikasi masih sangat terbatas, sedangkan untuk zaman kini, keempat hal tersebut sudah terpenuhi secara luar biasa canggihnya.
Agama Islam yang lahir di tengah-tengah pertarungan peradaban antara Romawi Timur dan Persia kiranya menawarkan alternatif peradaban lain. Jadi, orientasinya bukan untuk membentuk imperium baru yang terpusat, melainkan tata peradaban ynag terserat di mana saja agama Islam masuk ke suatu komunitas atau wilayah tertentu. Keterpusatannya adalah dalam “iman yang bekerja dalam setiap diri muslim”, bukan diwujudkan dalam wilayah daratan, tempat atau kota tertentu, atau kelembagaan tertentu. Dengan lain perkataan tata peradaban yang ditawarkan agama Islam adalah tata peradaban yang imanen dalam gerak hidup manusia muslim di mana saja tinggal dan hidup. Daya pemusatannya, kalau terpaksa harus dipaksakan begitu, semata-mata diikat oleh kekuatan kegiatan keagamaan (seperti tersirat dalam kegiatan berjamaah salat, berkumpul di padang Arafah ketika melaksanakan ibadah haji, kegiatan silaturrahim, ucapan salam dan sebagainya), bukan dalam wujud kekuatan politik (dengan didukung kekuatan militer) atau kekuatan ekonomi (yang sering dipilari oleh kekuatan sistem).
Untuk umat Islam pada abad ke-21 ini minimal, mestinya mempertimbangkan peta peradaban yang telah diteladankan pada zaman Rasulullah Saw di atas, tentu saja tanpa meninggalkan modifikasi yang relevan dan yang dipandang perlu. Umat Islam dewasa ini menghadapi “Romawi Timur” dan “Persia” yang baru. Eropa-Amerika telah mencengkeramkan peradaban tertentu yang sama-sama telah kita rasakan kegunaan dan dampaknya seperti sekarang ini. India-Cina telah mulai dibaca sebagai kekuatan peradaban yang lain lagi yang tampaknya sedang bergerak. Dalam hal seperti ini menurut penulis, peradaban Islam yang ditawarkan tetap perlu berbasis pada “keyakinan agama”, bukan ideologi. Yakni, basis keyakinan yang secara terus menerus diijtihadi untuk berhasil menjadi rumusan-rumusan yang berkadar sebagai “ilmu” (logis, konkret, empiris) seperti yang dikatakan oleh Kuntowijoyo (2004: 81-83). Kalau keberhasilan Cina didasarkan oleh ideologi yang disebut “ekonomi pasar sosialis”, sudah tentu bagi umat Islam yang ditawarkan harus lebih daripada sekedar “ideologi”, melainkan “ilmu” atau “objektivikasi” Islam yang dikenal sebagai din (dunia-akhirat, keuntungan-pahala, kesejahteraan-surga, material-spiritual), bukan sekedar agama dalam arti umum. Maka objektivikasi yang menghasilkan konsep-konsep yang terukur (logis, konkret, empiris) terhadap istilah-istilah agama Islam, seperti istilah “pahala”, “jamaah”, “birr”, “taqwa”, “amanah”, dan sebagainya.
Kapitalisme, sosialisme, komunisme, materialisme, hedonisme, dan isme-isme lain, adalah kebanyakan produk falsafah yang bahan dan sasarannya adalah realitas kehidupan dan alam semesta yang “terbuka” ini. Kalau kita disiplin memakai istilah Islam sebagai din di atas, maka mestinya produk-produk konsepnya akan lebih unggul dan lebih komperhensif, biperspektif (berperspektif kutub ganda). Itulah yang perlu tetap menjadi roh seluruh proses konseptualisasi ajaran Islam dalam kehidupan.
III
Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, sebagaimana dikutip oleh Simuh, kebudayaan dunia ini kalau dibelah dapat dibedakan secara tajam menjadi 2 (dua), yaitu: progresif dan ekspresif. Budaya progresif memiliki faktor-faktor yang meliputi ketinggian nilai ekonomi, teori (ilmu pengetahuan), dan kuasa (politik dan militer). Sedangkan budaya ekspresif memiliki faktor-faktor yang meliputi ketinggian nilai seni, keagamaan, dan solidaritas sosial (Simuh, 2003: 2-4; 13). Eropa dan Amerika (juga demikian Jepang yang kemudian akan disusul India dan Cina) menonjolkan nilai-nilai yang ada dalam budaya progresif di atas. Karena itu, mereka mengejar dan mengumpulkan kekuatan ekonomi (yang garda depannya adalah kekuatan ekonomi korporasi yang berorientasi pasar), kekuatan ilmu pengetahuan (dengan mengutamakan penelitian dan pengembangan, research and development dengan pendanaan cukup), dan kekuatan politik dan militer dalam skala global (menggalakkan lobi-lobi politik global dan penguatan perlombaan persenjataan). Etos yang bercorak budaya progresif inilah yang sekarang masih dijadikan patokan bagi negara-negara Barat dan negara-negara maju.
Sebenarnya roh budaya progresif ini secara tersirat telah ada dalam muatan Rukun Islam maupun ilmu-ilmu pendukungnya. Sebagai contoh, kewajiban zakat dan haji sesungguhnya mendorong secara langsung maupun tak langsung agar umat Islam menjadi “manusia kaya/berkecukupan”. Jadi kewajiban haji dan zakat mendorong masyarakat muslim menjadi masyarakat yang “berekonomi kuat”. Contoh lainnya adalah ilmu pendukung terhadap kewajiban shiyam Ramdhan dan pembagian harta warisan. Di sana ada ilmu falak (astronomi) dan ilmu faraidl yang keduanya memerlukan proses menghitung. Di sana diperlukan ilmu matematika, aritmatika dan goneometri. Dengan demikian ilmu eksakta memiliki posisi penting di sini. Ini sekedar contoh. Bahwa manakala kekuatan ekonomi umat Islam dapat digabungkan dengan kekuatan ilmu pengetahuan (terutama ilmu eksakta), maka akan menjadi kekuatan yang bisa dibelokkan ke arah kekuatan politik dan militer. Sementara itu, untuk kekuatan budaya ekpresif, agama Islam di samping telah memiliki konsep-konsep yang kaya, juga telah menjadikan kebiasaan hidup umatnya. Kalau digabungkan menjadi satu, maka kekuatannya akan menjadi sangat dahsyat, yang menurut Simuh diberi ungkapan “Islam sebagai kebudayaan yang paripurna:” (Simuh, 2003:7)
Jadi, untuk penyeimbang keadaan dewasa ini, maka umat Islam perlu merumuskan etos atau pandangan hidupnya minimal tentang penguatan nilai ekonomi, teori dan kuasa sebagaimana telah ditunjukkan oleh kekuatan bangsa-bangsa Barat dan bangsa-bangsa maju lainnya. Dengan lain kata, umat Islam perlu beretos budaya progresif.
IV
Khusus untuk umat Islam di Indonesia, perlu dipetakan dulu keadaannya. Ada beberapa keunikan dan sekaligus dapat dijadikan modal yang baik tentang masuknya Islam ke Nusantara ini. Pertama, menurut M. Abdul Karim, masuknya Islam ke Nusantara disebarkan secara penetration pacifique (damai), yaitu dengan apa yang disebut dengan da’wah bi al-hal, yang kemudian terjadi proses akulturasi antara Islam dan budaya setempat (Karim, 2011:1). Kedua, Nusantara dikenal sebagai taman sari agama-agama. Sebab, di Nusantara inilah, kata C.J. Bleeker, agama-agama seperti Hinduisme, Budhisme, Konfusianisme, Kristen (Katolik dan Protestan), dan Islam telah bertemu berabad-abad yang lalu. Pertemuan itu, menurut C.J. Bleeker, memberikan kemungkinan untuk ”saling belajar” dan saling memberikan “kontribusi” untuk kesejahteraan bersama karena agama masih merupakan tenaga penggerak yang kuat di wilayah Nusantara ini, umumnya Asia Tenggara (Bleeker, 1964: 108-109, 110). Ketiga, agama Islam mampu masuk ke dalam hampir seluruh wilayah Nusantara lewat kegiatan dagang dan lingua franca. Dari sini memungkinkan terjadinya rasa kesatuan bangsa, merasa seagama dan menekan/menepiskan fanatisme kesukuan. Ini semua lantaran makin menguatnya akulturasi agama Islam denagn budaya lokal. Memang sangat mungkin terjadi Islamisasi budaya lokal, tapi memerlukan waktu yang sangat panjang dan penuh kesabaran serta ketekunan.
Dengan adanya keunikan dan sekaligus modal yang baik di atas, maka penumbuhan etos di kalangan umat Islam tampaknya akan akan bertumpu atas berhasil-tidaknya umat Islam merumuskan karakter yang akan dijadikan dasar bekerjanya etos tersebut dalam seluruh tatanan pandangan hidup umat Islam dalam menghadapi pengaruh-pengaruh, tantangan bahkan ancaman dari luar. Dalam hal ini penyapaan konsep-konsep yang berasal dari Islam terhadap konsep-konsep kearifan lokal. Misalnya konsep “niat ibadah”, rahmatan li al-‘alamin”, “mencari pahala”, “amal saleh”, dan sebagainya disapakan dengan ungkapan-ungkapan seperti “rawe-rawe rantas, malang-malang putung” (semua yang merintangi diperkecil dan yang menghalangi dipotong putus; ungkapan Jawa), “etembang pote mata ango’ poteya tolang” (dari pada putih mata lebih baik putih tulang; ungkapan Madura), “bacak mati mandi khah, jak hokhek kena jajah” (lebih baik mati mandi darah, dari pada hidup kena jajah; ungkapan Lampung); “malai bukurupa ricaue, mappa limbang ri maje ripanganroe” (memalukan kalau dikalahkan, mematikan kalau ditaklukkan; ungkapan Bugis); “haram manyarah waja sampai ka puting” (pantang untuk menyerah sebagaimana baja dari pangkal sampai ujung; ungkapan Banjar); cenik-cenik kedis belatuke, nyidayang ngesongin kayu” (kecil-kecil burung pelatuk, dapat melubangi kayu; ungkapan Bali); “monang mangalo musuh, talu mangalo dongan” (kepala musuh kita harus menang, kepada teman kita harus mengalah; ungkapan Batak) (Santosa, 2008: 145, 146, 152), “marantaulah bujang dahulu, di kampung paguno balun” (carilah pengalaman dahulu wahai para pemuda, karena pengalamanmu belum memadai untuk disumbangkan kekampungmu; ungkapan Minangkabau) (Djohan, 1970:5), dan sebagainya.
Penyapaan konsep-konsep tersebut dipandang perlu, kalau mengikuti hasil pengamatan C. J. Bleeker, karena dengan adanya proses pertemuan agama-agama besar dunia di atas berdampak kecenderungan untuk dihargai eksistensi bagi masing-masing agama menjadi justru menaik. Dengan demikian penguatan terhadap ciri khas masing-masing agama menjadi makin menguat. Dari sinilah perlunya saling menghargai dan masing-masing agama akan merasa terhormat kalau disapa, didengar pendapatnya, diperhitungkan keberadaannya, dan sebagainya. Hal ini perlu diungkapkan, sebab pada hakikatnya pembentukan etos adalah tidak untuk kepentingan kelompok sosial terbatas, melainkan diharapkan dampak hasilnya untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dan bangsa. Toh menghargai agama lain tersebut tidak ada ruginya, bahkan al-Qur’an sendiri mengajarkan bersikap seperti itu (QS al-Kafirun, 109: 6)
Wallahu a’lam bishshawab.
DAFTAR BACAAN
Ali, H. A. Mukti, Agama dan Pembangunan di Indonesia, Jilid VI (Jakarta: Biro Humas Departemen Agama RI, 1975)
Asy’arie, Musa, Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Yogyakarta: LESFI, 1997)
Bleeker, C. J., Pertemuan Agama-agama Dunia, Terjemahan Barus Siregar, (Bandung: Penerbit “Sumur Bandung”, 1964)
Djohan, Bahder, “Manusia Minang sebagai Suatu Fenomena Socio-Biologik”, Makalah (Padang: tidak diterbitkan, 1970)
Karim, H. Muh. Abdul, Dialog: Persoalan Jalur Masuknya Islam di Indonesia (Studi Teori India: Bangla dan Gujarat)” Makalah, (Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2011)
Khan, Majid ‘Ali, Muhammad SAW Rasul Terakhir, Terjemahan Fathul Umam, (Bandung; Penerbit Pustaka, 1985)
Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika, (Jakarta:Penerbit Teraju, 2004)
Santoso, Imam Budhi, Budi Pekerti Bangsa, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008)
Sardar Ziauddin, Tantangan Dunia Islam Abad 21 Menjangkau Informasi, Terjemahan A.E Priyonon dan Ilyas Hasan, (Bandung: Penerbit Mizan, 1991)
Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini, Terjemahan A. M Saefuddin, (Jakarta: LIPPM - Media Dakwah, 1986)
Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003)
Welirang, Franciscus, Reviitalisasi Republik, Perspektif Pangan dan Kebudayan, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007)
Tags: etos , muslim , tarjih , muhammadiyah